
tempatnya bekerja.
KOPI, Jakarta – Jagat hukum riuh. Gegaranya, Baiq Nuril (BN) — korban pelecehan seksual asal NTB – terpaksa tetap divonis bersalah. MA kembali memutuskan BN bersalah: melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU ITE.
Kini, ibu tiga anak ini harus mendekam di penjara 6 bulan dan membayar denda Rp 500 juta. Tak ada upaya hukum lagi untuk mengubah keputusan hukum MA bagi BN. Keputusan yang diketok MA 4 Juli 2019 itu merupakan hasil akhir PK (Peninjauan Kembali) yang diupayakan BN — setelah sebelumnya Kasasi memutuskan BN bersalah. Kini satu-satunya yang bisa membebaskan BN adalah Grasi Presiden. Tapi ingat untuk memutuskan grasi, Presiden pun harus minta pendapat Menkumham dan DPR. Prosesnya panjang.
Kilas Balik
Tahun 2012, BN, pegawai honorer di SMAN 7 Mataram sering menerima telepon dari Muslim, kepala sekolahnya yang kerap bercerita soal hubungannya dengan wanita lain yang bukan istrinya. BN juga sering dipanggil Muslim ke ruangannya untuk mendengarkan ceritanya yang cabul. Tujuannya jelaslah, Muslim ingin sesuatu dari BN. Akibatnya BN tertekan. Ia merasa dilecehkan.
Secara diam-diam BN merekam pembicaraan atasannya yang cabul tersebut. Rekaman itu mulanya hanya disimpan di dalam handphone milik BN. Dua tahun kemudian, Desember 2014, BN didesak kawan-kawannya untuk menyerahkan rekamannya. Awalnya ia menolak, namun karena beberapa kali dibujuk akhirnya ia luluh dan menyerahkan HP berisi rekaman perbincangannya kepada IM, salah satu rekannya. IM dan rekan-rekan guru melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan. Rekaman perbincangan yang direkam itu menyebar. Alhasil, karier Muslim sebagai kepala sekolah tamat. Ia dimutasi. Muslim marah. BN pun dipecat Muslim dari pekerjaannya. Muslim pun melaporkan BN ke polisi.
“Semua sudah dihapus, flashdisk sudah dibuang. Sudah
damai waktu itu, cuma dia masih marah karena dimutasi itu. Akhirnya dia melapor
ke Polres Mataram. Dari Polres Mataram itulah proses hukum dimulai,” kata
Isnaini, suami BN (5/11/2017). Bahkan saat sang kepala sekolah dimutasi,
keluarga Nuril dan pihak sekolah ke rumah Muslim untuk meminta maaf dan
berdamai.

Muslim memaafkan namun proses hukum terus berjalan. Muslim tak mencabut pengaduannya. Akibat laporan tersebut, Nuril harus menjalani pemeriksaan di kantor polisi hingga akhirnya resmi ditahan pada 27 Maret 2017. Saat Nuril ditahan, Isnaini, suami Nuril terpaksa berhenti dari pekerjaannya dari salah satu rumah makan di Gili Trawangan karena harus mengurus ketiga buah hatinya yang masih kecil.
Di PN Mataram, Nuril dituduh jaksa mendistribusikan atau mentransmisikan rekaman pembicaraan Muslim menggunakan alat elektronik berupa ponsel merek Nokia miliknya ke laptop milik Imam Mudawin, rekan kerjanya. Perbuatannya ini, menurut jaksa, menyebabkan terhentinya karir Muslim sebagai kepala sekolah. Keluarga besar Muslim pun dipermalukan. Tapi hakim PN Mataram bersikap bijak dan melihat perkaranya secara substansial. PN Mataram pun memutus BN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. BN pun bebas.
Tapi jaksa tak menerima putusan hakim. Jaksa mengajukan
kasasi ke MA, 26 September 2018. Dan MA memutuskan BN bersalah, melanggar UU
ITE. BN tidak terima. Ia mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke MA. Hasil
akhirnya, kita tahu: Baiq Nuril tetap dianggap bersalah (4/7/019). Ibu 3 anak
yang masih kecil-kecil ini harus mendekam di bui enam bulan dan membayar denda
Rp 500 juta.

Salahkah Hakim MA
Pertanyaan yang mencuat: Salahkah tiga hakim agung MA yang memutuskan BN tetap melanggar UU ITE Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1? Bunyi kedua UU tersebut (disingkat penulis): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Secara tekstual, putusan PK MA itu “benar”. Tapi substansinya keliru. Orang Jawa menyebutnya: keputusan tersebut “bener ning ora pener”. Hakim Kasasi MA terjebak pada narasi literalnya, tidak melihat substansi kontekstualnya.
Kenapa? MA tak melihat konteks permasalahannya. Ia tak mempertimbangkan asal-usul kenapa Nuril melakukan hal tersebut. MA juga tak mempertimbangkan latar belakang Muslim dan apa tujuannya mengundang Nuril dan membicarakan hal-hal jorok dan tabu di atas. Jika hakim melihat konteks dan substansinya, niscaya keputusan dzalim itu tak akan diketuk.
Itulah permasalahan hukum, berayun antara teks dan konteks;
antara literal dan substansial. Dalam konteks inilah, seperti dikatakan Prof.
Mahfud MD, keputusan hukum harus mengacu pada etika dan moral. Tanpa etika dan
moral, hukum menjadi kering, melenceng, dan acap disalahgunakan.

Khalifah Umar Bin Khatab, misalnya, pernah membebaskan seorang pencuri. Padahal Nabi Muhammad pernah menyatakan, seandainya Fatimah, putri kesayangan Rasul, kedapatan mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tapi Umar membebaskan sang pencuri karena melihat konteksnya. Ia mencuri karena kemiskinan dan keluarganya kelaparan. Tragisnya, tetangganya diam dan pemerintah setempat tak memperhatikan dan menyantuninya. Keputusan Umar yang terkenal adil ini, kemudian menjadi jurisprudensi dalam fiqih (Hukum Islam). Dari konteks inilah seharusnya kasus Nuril dilihat MA.
Fenomena diskontinuitas antara teks dan konteks dalam hukum ini terjadi juga dalam memahami teks-teks ayat suci. Perintah membunuh orang kafir, perintah jihad, dan perintah memerangi kaum liyan agama dalam teks-teks kitab suci, misalnya, sering dibaca apa adanya tanpa melihat konteks. Akibatnya, ada orang yang mencari “keuntungan” politis dan kekuasaan dengan memanfaatkan teks-teks kitab suci tersebut. Padahal, sejak awal – misalnya di Islam – Alquran mendasarkan hukumnya pada keadilan dan kemanusiaan. Umar telah memberi contoh yang baik sekali dalam memutuskan hukum seperti cerita di atas.
Hilangnya konteks dalam memahami kitab suci itu berakibat
pada timbulnya konflik berkepanjangan antara “kaum tekstual” dan “kaum
substansial”. Kekacauan yang acap muncul dalam kasus SARA, misalnya, biasanya
diprovokasi “kaum tekstual” ini. Persis seperti gejolak kasus BN. Muslim secara
koinsidensi, misalnya, seperti bersepakat dengan hakim MA, menyalahkan Nuril
berdasarkan teks-teks literal yang tidak kontekstual dengan UU ITE tadi.

Kini nasi telah menjadi bubur. Tinggal Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan yang bisa membebaskan BN dari jeratan hukum melalui grasi. Kita berharap Presiden Joko Widodo melalui kewenangan yang melekat pada jabatannya, bisa memberikan keadilan pada kasus BN.
Belajar dari kasus Nuril dan Muslim, tampaknya DPR perlu merevisi UU ITE sedemikian rupa, agar pasal per pasal maupun ayat per ayat secara tekstual mampu “memaksa” aparat hukum untuk masuk dalam ranah etika dan moral yang kontekstual dengan kasusnya ketika memutuskan suatu perkara hukum. Jangan ada celah tekstual dalam UU ITE yang menjadikan penegak hukum bisa berkelit untuk memutuskan “sesuatu yang salah menjadi benar atau sesuatu yang benar menjadi salah”.
Kita harus ingat, keadilan adalah penyangga kehidupan di jagad raya. Dalam adagium hukum berlaku: meskipun langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan!
Penulis: Simon Syaefudin adalah Tenaga Ahli DPR-RI Fraksi PPP

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini












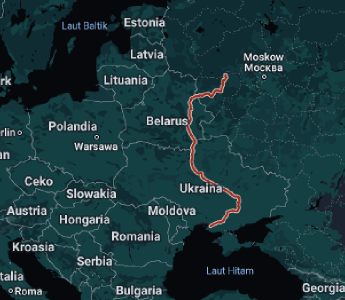














Comment