Review Buku Denny JA: Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim

Oleh: Prof. Lili Romli
Pengantar
Buku Denny yang berjudul “Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim: Indonesia Sebagai Model?” patut mendapat apresiasi, meski memang dalam pembahasan tentang peta jalan tentang demokrasi dan kebebasan untuk dunia muslim belum banyak dielaborasi.
Sebab secara defacto dan dejure, mayoritas dunia muslim masih berkubang dalam sistem otoritarian dan monarki absolut, yang juga sudah disampaikan oleh penulis sendiri. Belum lagi, yang juga dipaparkan, bahwa Arab Spring, yang semula dapat menggulingkan rezim otoriter, dalam perkembangannya musim semi demokrasi tidak berjalan ke arah pemerintahan demokratis, alih-alih kembali ke sistem semula (otoriter), hanya Tunisia yang berhasil menegakkan demokrasi.
Penulis buku ini tidak panjang lebar mengelaborasi, bisa jadi, mungkin sebagai pancingan bagi pembaca lain untuk lebih jauh memetakan jalan demokrasi dan kebebasan bagai dunia muslim.
Terlepas dari itu, buku Denny JA ini, yang diakui sebagai provokatif, merupakan gagasan yang genuine karena berani dan dengan penuh optimisme menyatakan bahwa negara-negara muslim akan bergerak ke arah negara-negara demokrasi.
Padahal sebagaimana diketahui, seperti dijelaskan dalam buku ini, berdasarkan Democracy Index 2019, dari 50 negara muslim yang diteliti tidak ada satu pun yang Full Democracy, sebaliknya mayoritas negara muslim masuk dalam kategori tidak demokratis/otoriter (30 negara), 17 negara masuk kategori Rezim Campuran (Hybrid Regimes), dan hanya 3 negara yang masuk kategori Flawed Democracy (demokrasi cacat atau belum matang), yaitu: Malaysia, Tunisia, dan Indonesia.
Optimisme ini perlu mendapat dukungan karena ia menepis pendapat Samuel P Huntington, Bernad Lewis, dan Ellie Kedourie. Ketiga sarjana ini tidak percaya akan adanya demokrasi di dunia muslim karena Islam bertentangan dengan demokrasi. Mereka mengatakan bahwa semakin kuat Islam dalam suatu masyarakat, demokrasi semakin tidak mungkin dapat dijumpai pada masyarakat tersebut (Mujani, 2007; 313).
Sebaliknya, seperti dikatakan oleh Huntington, budaya yang cocok untuk demokrasi adalah budaya Barat: demokrasi modern bermula di Barat, dan sejak awal abad ke 19, bagian terbesar negeri demokratis adalah negeri-negeri Barat (Huntington, 1995; 386).
Atas dasar itu tidak heran bila salah satu faktor yang mendorong lahirnya demokrasi, ia memasukkan agama Protestan sebagai faktor.
Meskipun demikian, Denny JA berpendapat bahwa pada waktunya mayoritas 50 negara muslim akan hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Menurutnya, gelombang besar peradaban bekerja lebih kuat dari rezim mana pun. Perjalanan menuju demokrasi dan kebebasan tetap akan terjadi meski berjalan secara bertahap.
Tentang tahap menuju demokrasi ini, Huntington (1995; 47) menyebutkan bahwa ada banyak faktor suatu negara akan menuju demokrasi, yaitu: Tingkat kemakmuran ekonomi secara menyeluruh tinggi; Distribusi pendapatan dan/atau kekayaan yang relatif merata.
Disebutkan juga ekonomi pasar: Perkembangan ekonomi dan modernisasi masyarakat; Tiadanya feodalisme dalam masyarakat; Borjuasi yang kuat; Kelas menengah yang kuat.
Syarat lain adalah tingkat melek huruf dan pendidikan yang tinggi; Budaya yang bersifat instrumental ketimbang idealis; Protestantisme; Pluralisme sosial dan kelompok-kelompok menengah yang kuat;
Berkembangnya kompetisi politik sebelum perluasan partisipasi politik.
Dalam sistem menuju demokrasi itu harus nampal pula struktur kewenangan demokratis di dalam kelompok-kelompok sosial; Tingkat tindak kekerasan oleh sipil yang rendah;
Tingkat polarisasi dan ekstremisme politik yang rendah.
Variabel lain: Pemimpin-pemimpin politik yang mendukung demokrasi dengan sepenuh hati; Pendudukan oleh suatu kekuatan asing yang pro-demokrasi; Pengaruh dari suatu kekuatan asing yang pro-demokrasi; Tradisi menghormati hukum dan hak-hak individu; Hasrat kelompok elite meniru bangsa-bangsa yang demokratis; dan Heteregonitas komunal (etnis, rasial, keagamaan)
Meski Huntington menyebutkan banyak faktor, untuk kasus di negara-negara muslim, gelombang demokrasi itu diharapkan oleh Denny seperti terjadi di Uni Soviet dan Blok Eropa Timur, di mana faktor pemimpin yang menentukan ke arah jalan demokrasi dan kebebasan tersebut, yang dipelopori Mikhail Gorbachev dengan Perestroika dan Glasnost. Berkat kepeloporan Gorbachev tersebut,
Denny menulis:
“Lihatlah Uni Soviet dan Blok Eropa Timur. Tahun 1946 sampai 1989- an itu wilayah komunisme. Jika kita melihat data kawasan itu di tahun 1970, misalnya, tentu hal yang mustahil membicarakan kemungkinan di kawasan itu beroperasi sistem politik dan ekonomi di luar komunisme.
Tapi lihatlah sekarang. Di kawasan itu, 29 negara sedang hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Kecepatan hijrah tentu berbeda-beda antar negara”
Denny mengatakan bahwa dengan terjadi demokratisasi di negara-negara muslim tersebut merupakan gelombang keempat. Ia mengatakan, “Kita sedang menunggu gelombang keempat demokrasi dan kebebasan.
Gelombang pertama dimulai oleh Inggris dan Amerika di abad 18-20. Gelombang kedua meluas setelah Perang Dunia II. Gelombang ketiga ketika melanda kawasan Komunisme Soviet dan Eropa Timur. Gelombang keempat ialah ketika melanda 50 negara muslim”.
Optimisme Denny terhadap gelombang demokrasi keempat yang nanti melanda negara-negara muslim perlu kita sambut dengan gembira. Karena memang negara muslim sebagaimana yang diperlihatkan oleh Democracy Index, yang dikutip dalam buku ini di mana sebagian besar masih otoriter dan bahkan 10 negara muslim lainnya tidak masuk dalam Democracy Index, suatu saat akan menuju ke arah demokrasi dan kebebasan.
Namun demikian, terhadap optimisme tersebut, tulisan ini mencoba memaparkan beberapa tantangan terklait demokratisasi dan kebebasan di negara-negera muslim, khususnya Indonesia, yang menurut Denny akan menjadi model demokrasi bagi dunia muslim.
Kelebihan Demokrasi
Dalam tulisannya Denny mengatakan mengapa ia memilih demokrasi bagi negara muslim, bukan sistem yang lain. Meski ada kekuarangannya, menurutnya dibanding sistem politik lain, demokrasi plus kebebasan terbukti dengan data lebih memajukan warga negara dengan seluruh dimensi.
Hasil berbagai riset, menurutnya, menunjukkan korelasi positif antara demokrasi, kebebasan, dan kebahagiaan warga negara.
Memang seperti dikemukan oleh beberapa ahli, demokrasi memiliki sejumlah kelebihan atau keunggulan. Robert A Dahl, misalnya, mengemukakan ada l0 hal keunggulan dari demokrasi dibandingkan dengan sistem lain yang tidak demokratis, yaitu (l) Menghindari tirani; (2) Hak-hak asasi; (3) Kebebasan umum; (4) Menentukan nasib sendiri; (5) Otonomi moral.
Keunggulan lain: 6) Perkembangan manusia; (7) Menjaga kepentingan pribadi yang utama; (8) Persamaan politik; (9) Mencari perdamaian; dan (l0) Kemakmuran (Dahl, 2001).
Leslie Lipson, dalam bukunya The Democratic Civilization, mencatat ada tiga argumen kuat yang membuat orang setuju terhadap demokrasi. Pertama, demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mengklaim menjunjung tinggi martabat manusia.
Kedua, mendorong terus menerus pendidikan kewarganegaraan (civic education). Ketiga, pendidikan tersebut membantu manusia agar lebih beradab (Lipson, 1964).
Meski ada sejumlah kelebihan dari demokrasi tersebut, dalam implementasi terdapat sejumlah distorsi, sehingga kemudian sebagian orang sangsi terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
Seperti yang dicontohkan oleh Denny dalam bukunya ini, di Indonesia misalnya, demokrasi bajak oleh sejumlah elite. Begitu juga dengan praktik demokrasi di negara-negara lain, sehingga tidak heran bila ada yang berkeberatan terhadap demokrasi.
Menurut Lipson (1964), ada tiga keberatan utama terhadap bentuk pemerintahan demokrasi. Pertama, tirani mayoritas. Yang dimaksud dengan tirani adalah perlakuan brutal terhadap sejumlah kecil orang oleh sejumlah besar orang dan penolakan terhadap hak-hak minoritas atau apa yang diyakini oleh minoritas sebagai hak-hak mereka.
Meski setiap tipe pemerintahan memerlukan kekuasaan dan kekuasaan dapat disalahgunakan, oleh minoritas, juga oleh mayoritas.
Kedua, bahwa demokrasi menempatkan orang yang bodoh di dalam kekuasaan. Padahal pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat, tetapi harus memiliki keahlian dan seni di dalam memerintah. Orang yang pintar itu memiliki kemampuan dan teknik-teknik memerintah. Harus juga selalu diingat bahwa secara alami hanya sedikit yang bisa memerintah dan massa harus bersedia dipimpin.
Ketiga, demokrasi adalah sebuah ilusi yang terbaik dan kebohongan yang jelek. Demokrasi di mana rakyat yang berkuasa adalah tidak mungkin. Rakyat tidak pernah berkuasa, bahkan tidak juga mayoritas, dan yang sebenarnya hanya beberapa saja yang memerintah. Pemerintahan yang bercirikan oligarki.
Demokrasi adalah dalih yang membantu untuk menyembunyikan dan melindungi beberapa orang. Oleh karena itu demokrasi hanyalah sebuah mimpi.
Islam dan Demokrasi
Dalam Islam, persoalan hubungan agama dan negara, termasuk di dalamnya hubungan Islam dan demokrasi, belum satu suara dan seragam dan satu pendapat. Masing-masing pemikir memberikan interpretasi dan pandangan yang berbeda terhadap hubungan agama dan negara, Islam dan demokrasi.
Persoalan ini sudah menjadi perdebatan yang lama dan panjang, yang sampai kini belum berakhir. Menurut Effendy, perbedaan itu terjadi karena memang dalam memandang sumber utama ajaran Islam (al-Quran dan al-Hadis) tidak bersifat monolitik, tetapi multi-interpretatif.
Munculnya berbagai interpretasi dan penafsiran atas teks sumber utama ajaran Islam tentu dipengaruhi oleh faktor waktu dan lingkungan yang bersifat teologis, historis, dan sosiologis. Akibatnya timbul berbagai interpretasi yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan satu sama lainnya. (Effendy, 1995).
Dalam konteks itu, para pemikir Islam menafsirkan hubungan antara agama dan negara juga berbeda-beda. Paling tidak, ada tiga pandangan tentang hubungan antara agama dan negara dalam Islam, yaitu:
Pertama, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (integrated); Kedua, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (simbiotik); dan Ketiga, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (sekularistik). (Syamsuddin, 1993).
Begitu juga terkait hubungan antara Islam dan Demokrasi. Seperti yang ditulis oleh Esposito dan Piscatori dalam artikelnya, “Democratization and Islam” yang diterbitkan Middle East Journal (45, No. 3., 1991) terdapat tiga corak pemikiran mengenai hubungan Islam dan demokrasi.
Pertama, Islam menjadi sifat dasar demokrasi, karena konsep syura, ijtihad, dan ijmak merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Kelompok ini mengatakan bahwa antara demokrasi dan Islam itu sama, baik dalam prinsip maupun prosedur.
Kedua, menolak bahwa Islam berhubungan dengan demokrasi. Kelompok yang menolak demokrasi menyatakan bahwa demokrasi tidak bisa dipadukan dengan Islam, bahkan ia merupakan ancaman yang perlu diwaspadai. Islam sudah cukup sempurna, untuk itu tidak perlu legislasi lain. Jika dalam demokrasi, kedaulatan rakyat bersifat mutlak maka dalam Islam kedaulatan mereka dibatasi oleh kedaulatan Tuhan.
Menurut pandangan ini kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri di atas kedaulatan Tuhan, juga tidak bisa disamakan antara muslim dan nonmuslim dan antara laki-laki dan perempuan.
Ketiga, sebagaimana pandangan pertama bahwa Islam merupakan dasar demokrasi. Meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan, perlu diakui bahwa kedaulatan rakyat tersebut merupakan subordinasi hukum Tuhan. Bagi kelompok ini, Islam dan demokrasi memang ada kemiripan dalam prinsip-prinsipnya, misalnya, keadilan, persamaan, musyawarah.
Akan tetapi keduanya berbeda dalam soal kedaulatan rakyat. Terma ini dikenal dengan theodemocracy yang diperkenalkan oleh Abul A’la al-Maududi (Esposito dan John O Vol, 1998).
Dalam buku ini Denny mengatakan bahwa pertanyaan apakah Islam dan demokrasi itu sesuai atau tidak? Apakah ajaran Islam dan nilai dasar demokrasi itu compatible? adalah “pertanyaan yang sia-sia karena Islam sebagaimana agama lain, dan konsep besar lain adalah wilayah interpretasi.
Selalu tersedia interpretasi dari ujung kiri, tengah hingga ujung kanan.” Sati sisi saya sependapat dengan Denny bahwa itu wilayah interpretasi, tetapi persoalannya interpretasi-interpretasi yang berbeda-beda tersebut di kalangan Islam banyak pengikutnya, tidak seperti di dalam agama Kristen, di mana persoalan interpretasi itu sudah selesai dan final.
Saya sendiri berpendapat bahwa Islam dan demokrasi, bukan hanya kompatibel tetapi suatu keharusan bagi negara-negara muslim untuk mengimplementasikan dan menerapkan demokrasi serta kebebasan. Karena merujuk kepada pendapat Fahmi Huwaidi, dalam bukunya Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, demokrasi dekat dan sejalan dengan Islam.
Beberapa konsep dan ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis Nabi, menunjukkan hal tersebut. Islam mengendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya, penolakan terhadap kediktatoran, dan dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelakyakan seorang kandidat dan mereka tentu saja, seperti diungkapkan dalam al-Quran, agar mereka tidak menyembunyikan persaksiannya, bersikap adil dan jujur serta tidak menjadi saksi-saksi palsu (Kamil, 2002).
Begitu juga dengan pemikir-pemikir lain seperti Soroush yang mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi antara Islam dan kebebasan—yang terkandung dalam demokrasi. Islam dan demokrasi tidak hanya sejalan, tetapi juga hubungan keduanya tak dapat dielakkan.
Ia membela demokrasi untuk dunia Islam bersandar pada dua pilar. Pertama, untuk menjadi mukmin sejati seseseorang harus bebas. Kebebasan ini merupakan dasar dari demokrasi. Demokrasi Islam tidak dapat dibentuk dari atas.
Demokrasi hanya diakui jika dipilih oleh mayoritas rakyat, meliputi kaum mukmin dan non-muslim (Wright dalam Sirry, 2002).
Al-Ghannouchi berpendapat bahwa demokrasi Islam awalnya merupakan penafsiran terhadap teks-teks kitab suci. Islam tidak datang dengan membawa program khusus berkenaan dengan hidup kita. Islam membawa prinsip-prinsip umum.
Kewajiban kita untuk membentuk program/sistem nilai melalui persentuhan antara prinsip Islam dan modernitas. Nilai-nilai demokrasi dari keberagaman politik dan toleransi secara sempurna cocok dengan Islam. Demokrasi Islam merupakan hasil pengalaman manusia belakangan. Kekuatan hukum negara Islam kontemporer berdasar pada kebebasan.
Tidak ada tempat untuk membuat perbedaan antar warga, dan hak-hak persamaan merupakan dasar bagi masyarakat muslim baru manapun (Wright dalam Sirry, 2002).
Begitu juga dengan para pemikir Islam di Indonesia, seperti yang ditulis oleh Masykuri Abdillah dalam buku “Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi”.
Para intelektual muslim Indonesia mengatakan bahwa dalam Islam terkandung prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti syura’ (musyawarah), al-‘adalah (keadilan), al-muawah (persamaan) dan ukhuwwah (persaudaraan). Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut ada dalam wilayah ijtihad (Abdillah, 1999: 307).
Di antara pemikir dan aktivis muslim yang paling gigih memperjuangkan demokrasi adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bagi Gus Dur, demokrasi merupakan manifestasi terbaik dari nilai-nilai luhur agama yang diyakininya. Dan dalam sistem demokrasi dimungkinkan umat dari berbagai agama, kepercayaan dan suku bisa bersatu untuk mewujudkan tujuan nasionalnya serta melindungi hak-hak asasinya.
Dalam dunia modern demokrasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju kedewasaan, kemajuan, dan integritas bangsa.
Demokrasi menjadi sedemikian penting dalam sebuah negara yang pluralistik karena ternyata perikehidupan kebangsaan yang utuh hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis.
Tantangan Demokrasi di Indonesia
Dalam bab yang lain Denny mengajukan preposisi bahwa Indonesia layak menjadi model, bukan saja karena Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berhasil mengalami pergantian kekuasaan berkali-kali melalui pemilu (pemilihan umum) yang damai, tetapi juga tumbuh kultur politik yang kuat tak ingin menjadi negara agama.
Lebih lanjut ia menulis beberapa alasan mengapa Indonesia layak sebagai model demokrasi di dunia muslim. Di bawah ini saya kutip langsung pernyataan Denny secara panjang lebar, yaitu:
“Pertama: di Indonesia, tidak terjadi kasus “One Man, One Vote, One Time”. Sejak reformasi tahun 1998, sudah berlangsung pemilu yang relatif aman berkali-kali. Pertama kali pemilu yang benar-benar bebas era reformasi di tahun 1999, lalu berlanjut setiap lima tahun: 2004, 2009, 2014 hingga 2019. Tak hanya pemilu legislatif yang berjalan teratur. Bahkan presiden juga dipilih langsung, dan sudah berkali-kali: 2004, 2009, 2014 dan 2019.
Dalam semua pemilu, relatif situasi politik terkendali. Tak pernah ada kasus pemenang pemilu ingin menghentikan pemilu berikutnya. Tak juga terekam pemenang pemilu ingin merusak kualitas pemilu berikutnya agar semakin tidak kompetitif, dan semakin tidak bebas.
Kedua: di Indonesia, perubahan kekuasaan terbukti bisa berlangsung dengan damai.
Pemilu adalah temuan peradaban modern di mana rakyat yangmenentukan siapa yang mereka inginkan untuk berkuasa. Peralihan kekuasaan selalu mungkin terjadi pada setiap pemilu. Di Indonesia sudah terjadi pergantian kekuasaan berkali-kali sejak reformasi.
Awalnya yang berkuasa Partai Golkar dengan Presiden Habibie. Kemudian beralih ke Presiden Gus Dur dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Beralih lagi ke Presiden Megawati dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Beralih lagi ke Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dari Demokrat. Kini beralih ke Jokowi dari PDIP. Tes sebuah stabilitas demokrasi memang pada perubahan kekuasaan itu. Di Indonesia, turn over kekuasaan itu berjalan lancar dan efektif.
Ketiga: di Indonesia, sungguh pun mayoritas penduduknya muslim, partai yang acap kali menang pemilu justru bukan partai yang berbasiskan agama. Yang selalu menang justru partai dengan platform keberagaman: PDIP, Golkar, Demokrat dan PDIP lagi.
Sejak pemilu reformasi, banyak partai lahir dan tumbuh. Sebagian mengusung simbol politik Islam. Bahkan pernah pula tumbuh partai yang mengkampanyekan akan menerapkan Syariat Islam”
Optimisme Denny bahwa Indonesia sebagai model demokrasi di dunia muslim perlu mendapat apresiasi dan dukungan, karena bukan saja seperti dikatakan Denny di atas sebagai penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, tetapi juga saya cermati bahwa seperti di dalam penelitian Saiful Mujani bahwa Islam mendorong para penganutnya untuk aktif dalam politik demokratis (Mujani, 2007).
Begitu juga dengan studi Hefner tentang Islam melalui organisasi Islam terbesar di Indonesia (NU dan Muhammadiyah) sebagai kekuatan civil Islam yang menopang demokrasi di Indonesia (Hefner, 2001).
Akan tetapi perkembangan yang muncul belakangan ini juga menjadi tantangan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dari sisi eksternal, dalam arti dari kekuatan non-Islam, demokrasi di Indonesia dibajak oleh para elite sehingga muncul politik dinasti di beberapa daerah dan juga oligarki politik baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan terhadap implementasi demokrasi itu sendiri.
Belum lagi ketika implementasi demokrasi itu diwujudkan dalam pemilihan umum (legislatif dan pemilihan presiden) dan pemilihan kepala daerah, yang muncul adalah sikap pragmatisme di kalangan elite politik dan maraknya money politics dalam setiap pesta demokrasi tersebut.
Sementara itu tantangan dari kalangan Islam Indonesia itu sendiri, apa yang dikatakan oleh Bruinessen sebagai conservative turn, kembali ke arah konservatif. Menurut Bruinessen, di dalam arus utama Islam (NU dan Muhammadiyah) di mana pandangan modernis dan liberal yang selama ini mendapat dukungan cukup luas kini kian ditolak.
Tanda paling jelas terjadinya conservative turn dapat dilihat dari sejumlah fatwa kontroversial yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menyatakan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama bertentangan dengan Islam (Bruinessen, 2014: 28)
Kontroversi yang lain ketika MUI mengeluarkan fatwa bahwa ucapan Ahok (Basuki Tjahya Purnama, Gubernur DKI Jakarta) masuk ke dalam kategori penistaan agama dalam Pidatonya di Kepulauan Seribu. Fatwa MUI ditanda tangani oleh Ketua MUI, KH. Ma’ruf Amin dan Sekjen MUI, Dr. H. Anwar Abbas.
Ada pun isi fatwa tersebut sebagai berikut (Detik.com, 2018):
- Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
- Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
- Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
- Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
- Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.
Dengan keluarnya fatwa MUI tersebut, lalu organisasi Islam yang dikoordinasi oleh FPI dan GNPF-MUI melaku-kan aksi demonstrasi pada hari Jumat 14 oktober 2016, yang menuntut pihak kepolisian untuk memproses laporan terkait Ahok.
Kelompok-kelompok Islam ini merasa tidak puas dan menganggap proses hukum lambat sehingga terkesan dilindungi oleh kekuasaan. Kemudian, aksi demo Aksi Bela Islam kembali digelar kedua kalinya pada 4 november 2016 yang bertajuk Aksi Bela Islam II (411) yang menuntut polri untuk menangkap Ahok dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Perkembangan kemudian muncul kembali aksi lanjutan yang diberi nama Aksi Bela Islam III yang lebih dikenal sebagai aksi damai 212. Aksi tersebut berpusat di Silang Monas dan meluber hingga ke Tugu Tani, kawasan Kwitang, Bundaran HI sampai Jalan Thamrin.
Secara sosiologis, peristiwa 212 merupakan gejala menguatnya konversatisme atau Islamisme di Indonesia.
Greg Fealy mengatakan bahwa peristiwa 212 menandakan kemenangan Islam garis keras di Indonesia. Hal ini dikarenakan motor penggerak dari aksi damai 212 tersebut adalah kelompok Islam yang terkenal keras seperti FPI (Front Pembela Islam) dengan tokohnya, Habib Rizieq Shihab.
Bahkan menurut Rosidi, memang dalam Aksi Bela Islam 212 ada berbagai kelompok, tetapi salah satu kelompok, yakni FPI dan HTI memiliki agenda tersendiri. Mereka memanfaatkan aksi ini sebagai alat atau saluran untuk agenda Islamisasi yang lebih luas. Mereka sejak lama bercita-cita mengusung Islamisasi Negara atau menerapkan Syariat Islam di berbagai lini kehidupan masyarakat Indonesia (Rosidi, 2016).
Gerakan Radikal
Tantangan lain bagi demokarasi Indonesia yang mesti diatasi adalah munculnya politik identitas. Seperti dikatakan Maarif, sejak 11 tahun terakhir era reformasi ini munculnya gerakan-gerakan radikal atau setengah radikal yang berbaju Islam di Indonesia.
Sebagaimana partner mereka di bagian dunia lain, gerakan-gerakan ini juga anti-demokrasi dan anti-pluralisme, dan sampai batas-batas yang jauh juga anti-nasionalisme.
Secara ideologis, mereka ini jelas mendapat inspirasi dan pengaruh dari gerakan Islamis dan Salafi yang semula berpusat di beberapa negara-negara Arab, kemudian dengan kecepatan tinggi menyebar ke seluruh jagat (Maarif, 2012; 21).
Sekalipun gerakan Islamis dan Salafi ini terdiri dari berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan yang sama: pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bernegara.
Kelompok-kelompok radikal ini, dengan kemungkinan perbedaan dan bahkan konflik di antara berbagai faksi di kalangan mereka, menurut Yusuf al-Qardhawi termasuk dalam kategori mazhab Zhahiriyyah baru dengan enam ciri yang menonjol: pemahaman dan penafsiran yang literal, keras, dan menyulitkan, sombong terhadap pendapat mereka, tidak menerima perbedaan pendapat, mengafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka, dan tidak peduli terhadap fitnah.
Al-Qardhawi menulis (Maarif, 2012; 25):
Orang-orang literal tersebut tidak cukup hanya dengan mengingkari orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, tetapi melakukan hal-hal lebih besar dari itu, yaitu dengan berburuk sangka, membid’ahkan, memfasikkan, dan sampai mengafirkan mereka.
Dasar bagi orang yang berbeda pendapat dengan mereka adalah ”tuduhan.” Padahal, menurut hukum manusia, dasar orang yang dituduh adalah, ”benar” (tidak bersalah). Inilah hal yang ditegaskan oleh Syari’ah Islam. Namun dasar bagi mereka adalah, tertuduh (bersalah) hingga terbukti.
Sementara menurut Musdah, jika kita menengok ke Tanah Air, yang digawangi oleh kelompok fundamentalis, telah melahirkan tiga bentuk kekerasan.
Pertama, kekerasan fisik seperti pengrusakan, penutupan tempat ibadah, seperti gereja dan masjid maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan obyek kekerasan tersebut menjadi terluka, trauma, maupun terbunuh.
Kedua, kekerasan simbolik, yang dapat berupa kekerasan semiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah yang bernada melecehkan suatu agama. Ketiga, kekerasan struktural, yang berbentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun aparatnya sendiri (Musdah, 2012; 45-46).
Di kalangan umat Islam Indonesia fundamentalisme agama cenderung menguat. Gelombang Islam transnasional yang membawa paham-paham radikal membuat kelompok-kelompok Islam fundamentalis semakin mengukuhkan dirinya.
Mereka tak segan-segan melakukan berbagai manuver untuk ”menyingkirkan” semua kelompok yang dianggap berbeda. Munculnya Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, dan beberapa kelompok sejenis termasuk ke dalam faktor penyebab ini.
Dukungan MUI atas gerakan ini semakin memperparah situasi, dengan melahirkan berbagai fatwa yang mendiskreditkan beberapa kelompok yang menurut mereka ”menyimpang”, hingga berujung berbagai kasus kekerasan (Musdah, 2015; 46-47).
Menurut Jones, pendukung gerakan radikal ternyata berasal dari masyarakat madani (civil society). Menurutnya, di Indonesia, tidak bisa bicara masyarakat madani tanpa memasukkan kelompok-kelompok Islam yang mendukung formalisasi syariat Islam dan berniat menggantikan sistem demokrasi dengan pemerintahan Islam.
Tujuannya bisa sangat sempit dan diskriminatif; doktrinnya bisa eksklusif, dan untuk beberapa, taktiknya bisa termasuk penggunaan kekerasan. Kunci untuk mempertimbangkan kelompok-kelompok ini sebagai masyarakat madani adalah apakah mereka melihat diri mereka sebagai jembatan antara warga negara dan negara, dan sebagian besar memang begitu (Jones, 2015; 7).
Ada tiga jenis kelompok garis keras yang berkembang di Indonesia yang anti demokrasi: pertama, kelompok main hakim sendiri, dan FPI adalah yang paling terkenal dalam kategori ini; kedua, kelompok advokasi di tingkat akar-rumput, bisa diwakili oleh GARIS (Gerakan Reformis Islam), sebuah organisasi akar-rumput yang cukup kaya di Cianjur dan dipimpin oleh Haji Chep Hernawan yang juga kerap menggunakan taktik kekerasan; dan
ketiga, kelompok transformatif yang diwakili oleh Hizbut Tahrir, yang ingin menggantikan sistem demokratik di Indonesia dengan khilafah (Jones, 2015; 8).
Azca mengajukan tiga varian utama gerakan Islam radikal yakni pertama, varian saleh; kedua, varian jihadis; ketiga, varian politik. Varian saleh lebih berorientasi kepada aktivisme pembangunan ‘moralitas individu’, mereka sangat concern dengan kegiatan-kegiatan dakwah seperti pendidikan dan kajian-kajian keislaman.
Termasuk ke dalam kelompok ini adalah FKAWJ, Salafi, dan gerakan Tarbiyah. Aktivis gerakan Islam radikal Jihadis menyetujui penggunaaan metode kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuan gerakannya. JAT, JI, dan DI adalah anggotanya.
Sedangkan aktivis Islam radikal politik adalah varian yang paling intensif terlibat dalam proses advokasi agenda gerakan mereka dalam ruang publik, sebagian dari mereka adalah PKS, PPP, PBB, HTI dan FPI (Azca, 2015; 56).
Perda Syariah dan Intoleransi Agama
Selain itu, pasca era reformasi, ketika diterapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, di beberapa daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syariat Islam, sehingga kerap disebut sebagai Perda Syariah.
Sejak tahun 1998 sudah terdapat 443 Perda Syariah yang diterapkan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, paling tidak ada empat macam atau jenis yang muncul. Pertama, perda yang terkait dengan isu moralitas masyarakat secara umum, seprti perda anti pelacuran, perzinaan atau anti kemaksiatan.
Kedua, perda yang terkait dengan fashion dan mode pakaian lainnya seperti keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu.
Ketiga, perda yang terkait dengan “keterampilan bergama:”. Seperti keharusan bica baca tuluis al-Quran. Keempat, perda yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat melalui perda zakat, infak dan shadaqah (Suadey, 2007, 27-28).
Meski demikian, dalam pembuatan perda syariah tersebut terselip juga kepentingan elite-elite politik dalam kaitan dengan politik elektoral. Michael Buehler, dalam wawancara dengan BBC Indonesia (21 Febriari 2017) mengatakan,
“Penerapan Perda Syariah di Indonesia tidak terlalu menjadi pertanda dari pergeseran/transformasi ideologis yang meluas dalam masyarakat Indonesia. Namun lebih sebagai hasil dari politik pemanfaatan.
Politisi yang butuh mobilisasi warga dalam konteks pemilihan umum kini mengandalkan kelompok-kelompok yang mendorong penerapan Perda Syariah. Politisi yang sebenarnya menerapkan perda itu bukanlah pegiat Islamis.
Saya juga meragukan mereka (politisi) benar-benar yakin pada Perda Syariah atau mengetahui banyak tentang itu. Politisi Indonesia yang menerapkan perda seperti itu, dengan kata lain, adalah Islamis oportunis”.
Dalam era reformasi ini muncul juga kasus-kasus intoleransi agama, yang pada umumnya didominasi oleh kekerasan dan penyerangan, penyebaran kebencian, pembatasan berpikir dan berkeyakinan, penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat, pembatasan aktivitas/ritual keagamaan, pemaksaan keyakinan, dan konflik tempat ibadah.
Sedangkan bentuk tindakan intoleransi yang paling banyak adalah penebaran kebencian terhadap kelompok, negara/bangsa tertentu; penyerangan, perusakan, dan penggerebekan rumah, bangunan, atau tempat ibadah; penolakan pendirian rumah ibadah; tuntutan penegakan syariat Islam; pengusiran, pemberhentian kerja, pelarangan kegiatan mirip agama lain, dan pemukulan.
Sejak era reformasi aksi-aksi kekerasan atas nama agama terus meningkat, dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Kasus-kasus pengeboman, pengrusakan tempat ibadah, pembubaran acara keagamaan dari kelompok yang dianggap sesat, sampai pada sweeping tempat-tempat hiburan dan warung makan yang buka pada bulan Ramadhan, merupakan beberapa contoh yang menjadi pemandangan yang biasa akhir-akhir ini.
Aksi main hakim sendiri yang umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras itu di satu sisi menunjukkan adanya degradasi kultur politik bangsa secara umum. Di sisi lain, kekerasan atas nama agama (Islam) juga menjadi fakta degradasi kultur di kalangan sebagian umat Islam sendiri.
Gejala intoleransi agama secara nyata bisa dilihat sebagai penggunaan agama untuk kepentingan politik. Politisasi agama atau instrumentalisasi ajaran agama untuk kepentingan politik kerap digunakan dalam pemilu legislatif, maupun pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden.
Politisasi agama muncul karena adanya pencampuradukan antara wilayah agama dan wilayah politik. Salah satu bentuk politisasi agama terkait dengan pemilihan calon kepala daerah atau presiden yang nonmuslim.
Sejumlah ulama, misalnya, menyatakan bahwa pemimpin yang korup masih bisa diperbaiki, sementara yang kafir sulit untuk diubah karena menyangkut akidah dan hidayah Tuhan. Mereka meyakini benar bahwa seorang pemimpin nonmuslim selalu dan selamanya akan merugikan, menghambat dakwah dan perkembangan Islam.
Catatan Penutup
Dalam kaitan dengan demokrasi di dunia muslim, termasuk di Indonesia, saya kira gagasan agar sebangun seperti demokrasi di negara-negara Barat, yang disebutnya sebagai demokrasi liberal, perlu menjadi cacatan.
Denny dalam buku ini menulis,
Terminal pertama yang akan dicapai oleh hijrah massal Dunia Muslim adalah demokrasi minus liberalisme. Ialah sistem politik dan ekonomi yang melaksanakan pemilu (pemilihan umum), tapi dengan sistem kebebasan terbatas.
Kultur kebebasan, yang sepenuhnya menjamin hak asasi manusia, tentu tak bisa diharap langsung tumbuh di kawasan ini. Demokrasi minus liberalisme adalah titik kompromi awal Dunia Muslim dan Dunia Barat.
Misalnya, hak kaum LGBT (Lebian, Guy, Bisexual, Transgender) untuk menikah dan disahkan negara. Kultur liberal ini tentu sulit diharap disahkan oleh negara muslim. Setidaknya itu tak akan terjadi pada tahap awal hijrah menuju demokrasi pada dekade 2020.
Saya kira gagasan untuk menerapkan demokrasi copy paste seperti di negara-negara Barat, yang disebutnya sebagai demokrasi liberal, dan jika tidak seperti itu dianggap demokrasi tidak liberal (illiberal), banyak intelektual muslim dan tokoh muslim tidak sependapat.
Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bahtiar Effendy, di mana harus meletakkan demokrasi dalam konteks budaya di mana kita berada. Proyek kontekstualisasi demokrasi ini berangkat dari kenyataan bahwa demokrasi merupakan konsep politik yang berasal dari luar Islam yang mempunyai dukungan budaya tidak luas (Prayitno, 2009; 31).
Dalam konteks itu, saya kira gagasan yang disampaikan oleh Alfred Stepan tentang perlunya twin toleration (toleransi kembar) sangat relevan bagi pengembangan demokrasi di dunia muslim, termasuk di Indonesia.
Dalam gagasan ini, otoritas keagamaan tidak mengontrol pemimpin yang dipilih secara demokratis, sementara negara juga harus mempertahankan adanya ruang bebas bagi agama (Bagir, 2014; 21).
Dalam konteks itu, copy paste demokrasi liberal untuk diterapkan di negara-negara muslim perlu ada adaptasi dan penyesuaian-penyesuian sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai yang mendasarinya. Seperti juga demokrasi itu sendiri, ada berbagai macam model-model demokrasi yang diterapkan di negara-negara Barat.(*)
Prof. Lili Romli, Lahir di Serang, Banten, Profesor Riset pada Pusat Penelitian Politik LIPI, staf Pengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP UI dan Pascasarjana Ilmu Politik UNAS serta Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Aktif melakukan penelitian tentang Partai Politik, Pemilu dan Pilkada, Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan, dan Otonomi Daerah.
Beberapa kali pernah menjadi Koordinator Penelitian tentang Partai, Pemilu dan Lembaga Perwakilan. Beberapa bukunya, antara lain, Islam Yes, Partai Islam Yes; Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal; Potret Partai Politik Pasca Orde Baru; Menggugat Partai Politik; Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru; Pemilu Era Reformasi; dan Sistem Presidensial Indonesia.
Ia juga menjadi kontributor beberapa buku, antara lain, Pengawasan DPR Era Reformasi; Masa Depan Partai Islam di Indonesia; Partai dan Sistem Kepartai Era Reformasi; Fraksionalisme dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi; Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi; dan Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi.
Daftar Pustaka
Abdillah, Masykuri, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
Al-Barbasy, Ma’Mun Murod, Politik Perda Syariat, Jakarta; Suara Muahammadiyah, 2018.
Azca, M. Najib, “Yang Madani Namun Intoleran?: Trayektori dan Variasi Gerakan Islam Radikal di Indonesia”,dalam Sidney Jones,Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia, Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta, 2015.
Bagir, Zainal Abidin, “Pengantar: Membaca Beragam Wajah Islam Indonesia” dalam Martin Van Bruinessen (editor), Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme, Bandung: Mizan, 2014
Bruinessen, Martin Van (editor), Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme, Bandung: Mizan, 2014.
Dahl, Robert A, Perihal Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 200l.
Esposito, John l. dan John O Vol, Demokrasi di Negara-negara Muslim problem dan Prospek. Bandung, Mizan, 1998
Effendy, Bahtiar. “Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia”, Prisma, No.5.1995.
Hefner, Robert W, Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia, Jakarta: The Asia Foundatian dan IASI, 2001.
Huntington, Samuel P, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1995.
https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya. Diakses, 2 Oktober 2018.
Jones, Sidney, “Sisi Gelap Reformasi di Indonesia Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran”, dalam Sidney Jones, Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia, Jakarta; Yayasan Wakaf Paramadina, 2015,
Kamil, Sukron. Islam dan Demokrasi, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
Lipson, Leslie, The Democratic Civilization, New York: Oxford University Press, 1964.
Ma’arif, Ahmad Syafii, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Jakarta; Democracy Project, 2012,
Mulia, Siti Musdah, Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia, Jakarta; Democracy Project, 2012.
Rosidi, Imron, “Muslim Saleh atau Radikal: Prospek Toleransi Agama di Indonesia Pasca 212”, Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2016.
Rozi, Syafuan (Ed.), Demokratisasi dan Pengelolaan Politik Identitas di Indonesia, Jakarta; Mahara Publishing dan P2P LIPI, 2016.
Saiful, Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta: Gramedua Pustaka Utama, 2007.
Suadey, Ahmad, Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia, Jakarta; The Wahid Institute, 2007. hal. 27-28.
Syamsuddin, Din 1993, “Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”, Ulumul Qur’an, No.2 Vol. IV.
Sirry, Mun’im A, Islam, Lebralisme, Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global, Jakarta: Paramadina, 2002.
Prayitno, Adi, Politik Akomodasi Islam, Percikan Pemikiran Politik Bahtiar Effendy, Jakarta: UIN Press, 2009
Wright, Robin, ‘Islam dan Demokrasi Liberal, Dua Visi Reformasi’, dalam Mun’im A Sirry, Islam, Lebralisme, Demokrasi, Jakarta: Paramadina, 2002.
-000-
Buku Denny JA: Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim bisa dibaca, download/cetak, disebar dari
https://www.facebook.com/groups/970024043185698/permalink/1324597131061719/

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini































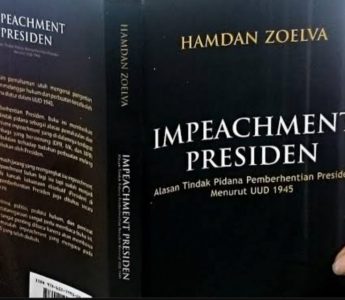





Comment