Sebuah Cerpen Esai (1)
KOPI, Jakarta – Teks itu singkat di japri WA-ku. Singkat tapi menyentak jantung. “Kak, aku sekarang dikarantina di Mesjid. Insha Allah, aku baik- baik saja. Titip istri dan anakku.”
Reflek saja segera aku call adikku, Iman, yang mengirim teks. Tak diangkat. Aku call lagi. Tak diangkat. Hingga tiga kali aku call. Selalu tak diangkat.
Aku membalas dengan teks: “Iman, angkat telp kakak.” Tapi teks itu juga tak kunjung dibaca.
Segera aku searching di Google. Media online sudah banyak memberitakannya. Sekitar 300 Jamaah Tabligh di Kebun Jeruk dikarantina. Mereka berasal dari berbagai daerah Indonesia. Sebanyak 78 orang warga negara Asing. (2)
Seluruh Jamaah dikarantina karena tiga orang ditemukan positif Virus Corona.
“Ampun,” aku mengeluh dalam hati. Ternyata satu kelompok jamaah, seluruhnya dikarantina.
Lima tahun sudah Iman memang bergabung dengan Jemaah Tabligh.
Segera kuhubungi istri Iman. Kuhubungi anak-anaknya berusia 9 tahun dan 7 tahun. Kutenangkan mereka.
Lama aku terdiam merenungkan Iman. Ia adikku tersayang.
Kutatap lukisan yang ia buat dua puluh tahun lalu. Lukisan ini kuletakkan di ruang keluarga.
Usiaku kini 57 tahun. Iman 46 tahun. Baginya aku tak hanya kakak sulung, tapi juga pengganti Ayah. Kami ditinggal Ayah ketika usiaku 21 tahun.
Lukisan ini moment ketika aku dan Iman di tepi sawah di kampung halaman dulu. Usia iman 7 tahun, saat itu usiaku 18 tahun.
Kakinya tergores luka terkena batu dekat sawah. Dari sawah hingga ke rumah, jaraknya mungkin 500 meter. Aku gendong Iman. Ia menangis kesakitan.
Ia kugendong dari belakang. Dua tangannya memegang leherku. Kaki kiri dan kaki kanannya aku bopong dengan tangan.
Berkali-kali, aku tenangkan. “Sudah dik, jangan menangis. Kakak selalu menjagamu.”
Momen itu ia lukis. Ia berikan ketika ia selesai wisuda. Iman tinggal bersamaku sejak aku menikah. Aku membiayai kuliahnya.
Yang membuatku terharu, di lukisan itu, ia tulis: “My brother is always my superhero.”
“Terima kasih Kakak,” ujarnya ketika memberiku lukisan itu. “Aku tak tahu bagimana membalas hutang budiku.”
Aku peluk Iman, Adikku. “Dik, tak usah kau dibebani hutang budi. Kau adikku. Nyawaku pun kupertaruhkan menjagamu.”
Iman menangis terharu. Iman memang sentimental. Ia mudah sedih. Mudah haru.
-000-
Malam itu, aku tak bisa tidur. Sungguh khawatir. Apakah Iman terkena Virus Corona? Masalahnya obat pemunah virus itu belum ditemukan.
Di dinding, jam menunjuk pukul 2.00 dini hari. Kucoba mengingat momen yang akhirnya membuat Iman bergabung dengan Jamaah Tabligh, lima tahun lalu.
Sejak kecil lalu selesai kuliah, hingga ia menikah dan punya anak, Iman bukan penganut agama yang taat. Sholat juga sangat jarang sekali.
Situasi berubah ketika istri pertamanya wafat. Kangker ganas merengut nyawa. Bagi Iman, istri itu cinta hidupnya. Mataharinya. “Lia itu Love of my life, Kak,” ujar Iman padaku.
Hampir sebulan Iman berduka. Ia bahkan jarang ke kantor. Aku mendengar ia sering menghibur diri ke night club. Minuman Keras. Mabuk. Main perempuan nakal.
Pernah empat mata, Ia kuajak bicara. “Iman, sampai kapan kau siksa dirimu. Lia sudah pergi. Apapun yang kau lalukan, Lia tak kembali.”
“Hidup terus berlanjut Dik. Dua anakmu masih kecil. Kau harus hijrah, Dik. Hidup begitu banyak kemungkinan. Cakrawala luas tak berbatas.”
“Jangan kau biarkan burungmu terkurung di sangkar. Kau buka pintu. Terbanglah tinggi. Mumpung kau masih muda.”
Di meja makan ini, di rumahku ini, Iman menelengkup. Ia menangis sesenggukkan.
Enam bulan kemudian, Iman datang lagi menemuiku. Ini sungguh Iman yang berbeda. Janggutnya panjang. Ia memakai baju Afganistan warna putih. Celananya cungkring. Tak lupa pakai peci putih. Ia bawa kayu siwa untuk membersihkan gigi.
Satu titik di keningnya agak hitam. Sepertinya ia sangat sering sholat yang membuat satu titik keningnya menghitam.
Aku kaget. “Iman, apa yang terjadi.” Tak hanya penampilan fisik Iman yang berbeda. Wajahnya pun cerah. Penuh keyakinan diri.
Singkat jawabnya. “Aku hijrah kak. Aku ikut Jemaah Tabligh.”
“Ha? Bagaimana duduk perkaranya? Kok jauh sekali hijrahmu. Dari satu ujung ke ujung lainnya?”
Imanpun bercerita berjumpa teman lama. “Aku merasa teman ini dikirim Tuhan menyelamatkanku,” jelasnya.
“Kok, kamu tak cerita sejak awal pada kakakmu. Aku ini bukan hanya kakakmu, lho! Aku pengganti bapakmu juga.”
“Maaf Kak,” ujar Iman. “Aku baru akan cerita setelah aku nyaman dulu di tempat baru ini. Sekarang aku sudah nyaman. Aku siap bercerita.”
Melihat Iman saat itu, perasaanku bercampur. Aku senang karena ia nampak kuat dan bahagia. Tapi aku juga khawatir. Apakah jalan Jemaah Tabligh ini memang pilihan sejati hidupnya. Aku tahu persis, sejak kecil hingga kematian istrinya, Iman ini hatinya sekuler. Liberal.
Imanpun cerita tentang hidup barunya di Jemaah Tabligh. Ia mengutip hadist, yang menyatakan perlu mengembangkan gaya hidup seperti Rasul. Itu yang membedakannya dengan komunitas lain.
Dalam setahun, ujar Iman, sekitar 40 hari ia cuti dari kantor dan keluarga, untuk berdakwah keliling. (3) Pusat Jemaah Tabligh ini di India. Anggota jemaah ada di 220 negara. Total jumlah anggota sedunia sekitar 140 juta.
Setiap kali mereka berdakwah di kota yang berbeda. Kadang juga berdakwah di manca negara. Mereka akan disambut oleh jaringan Jamaah Tabligh di kota itu.
“Bulan depan, aku akan menikah lagi, Kak,” info Iman. “Yang benar? Siapa calon istrimu? Kok tak dirimu perkenalkan dengan kakak dulu?” tanyaku menggoda.
“Amir yang memilihkan untukku. Aku baru jumpa sekali dengan calon istri. Pun aku tak tahu persis wajahnya. Ia bercadar penuh. Hanya matanya yang nampak. Tapi aku percaya Amir (4).
Amir adalah julukan pemimpin di kalangan Jamaah Tabligh untuk satu wilayah. Mereka diajar untuk tunduk penuh pada Amir. Kecuali jika Amir mengajak ke jalan yang bertentangan dengan Islam.
Iman juga bercerita. Tradisi makan di Jemaah ini juga unik. Dalam pertemuan, 5-7 orang duduk di hadapan nampan besar makanan. Mereka makan bersama dalam satu nampan, dengan tiga jari tangan.
Dengan bangga, Iman cerita. Betapa di Jamaah Tabligh, kesetaraan manusia dan kekeluargaannya begitu kuat. Jenderal atau kopral, konglomerat atau buruh, ulama atau mantan preman, duduk bersama setara makan di nampan. (5)
“Iman,” kataku. “Dirimu tahu sikap kakakmu. Aku menyayangimu. Tapi hidupmu adalah milikmu. Kau pilih saja hidup yang memang sesuai dengan jiwamu.”
“Tapi satu pesan kakak,” tegasku. “Jangan kau matikan pikiran kritismu. Selalu buka cakwalamu. Hidup itu seperti pelangi. Ia warna dan warni. Renungkan ya.”
-000-
Kami kakak adik bertiga. Aku Darta, kini 57 tahun. Iman 46 tahun. Tapi Iman punya kakak berselisih dua tahun saja, Wahib, 48 tahun.
Baik bagi Iman ataupun Wahib, aku kakak sulung sekaligus penganti bapak. Ibu sudah wafat 10 tahun lalu.
Tapi Iman dan Wahib sangat tidak akur. Mungkin karena selisih usia mereka hanya dua tahun.
Setahun lalu, juga di meja makan ini, Iman dan Wahib bedebat soal agama. Berbeda dengan Iman yang latar belakangnya insinyur, Wahib ini lulusan sekolah agama. Ia Ph.D di Amerika Serikat bidang studi Islam.
Sedangkan Iman belajar Islam otodidak, dan dari komunitas serta Amir.
Ujar Wahib, keras sekali. “Iman, cara dirimu meniru Rasul itu nanggung. Kok hanya pakaian dan prilakunya yang ingin ditiru. Mengapa tidak lebih jauh. Misalnya kau juga naik Onta. Kan Rasul naik Onta.”
“Juga jangan pakai Handphone. Kan Rasul tak pakai Handphone. Yang kau ambil itu abu bukan api dari Islam.”
Iman tak kalah sengit. “Wahib, kita hanya berbeda guru saja. Tapi kita berdua sama militan. Aku militan dengan Amirku. Dirimu militan dengan profesor Amerikamu yang sekuler dan liberal.”
“Lagi pula, bagaimana kau bedakan mana yang abu mana yang api Islam?Itu kan tafsirmu semata. Jangan- jangan yang api bagimu, sebenarnya hanyalah abu!” seru Iman.
“Api islam itu nilai Quran,” tegas Wahib. “Sudah ada Islamicty Index yang mengukur nilai Islami. Ternyata nilai Islam itu lebih tumbuh di Barat.”
“Pemerintahan yang bersih, Ilmu pengetahuan yang maju, program kesejahteraan rakyat, perlindungan pada kebebasan, itu nilai Islami.”
“Itulah Api Islam. Dan Itu ada di dunia barat yang memakai jas dan rok mini. Jenis baju tak penting amat. Tumbuh janggut atau kumis, itu bukan masalah utama.”
Seperti biasa aku selalu merelai. Jika debat intelektual, pastilah Iman tak bisa mengimbangi kakaknya yang memang doktor bidang keislaman.
Tapi Wahib berhenti sebagai ilmuwan. Bagi Wahib, agama sekedar obyek studi. Sementara bagi Iman, agama itu jalan hidup. Pada Iman lebih terasa girah agama.
-000-
Sore itu aku panggil Wahib. Aku ingin teman diskusi untuk nasib Iman.
“Wahib, coba jelaskan ke kakakmu, apa yang sebenarnya terjadi?”
“Kak,” ujar Wahib. “Jamaah Tabligh ini medium Virus Corona di banyak negara. Tidak hanya di Indonesia. Tapi juga di India, Malaysia, Pakistan, bahkan di Amerika Serikat.” (6)
“Mengapa seperti itu? Apa yang ada di Jemaah Tabligh dibandingkan ormas lain, yang membuatnya lebih menularkan virus?” tanyaku sangat ingin tahu.
“Dua hal, Kak,” jawab Wahib. Pertama itu sikap pemimpin internasionalnya di India. Ia tetap mengajak jemaah di seluruh dunia untuk berkumpul di mesjid.
Ujarnya, “Jika gara-gara virus kita mati di mesjid, maka mesjid adalah tempat paling baik untuk mati.”
“Kedua, dalam pertemuan Jamaah Tabligh itu, setiap 5-7 orang makan bersama dalam satu nampan. Mereka makan tak pakai sendok. Langsung dengan tangan. Bisa dibayangkan, jika satu terkena virus corona, 5-7 orang lainnya tertular.”
“Waduh.” Hanya itu komentarku.
Media online memberitakan, sebagian Jamaah Tabligh sudah dipindahkan ke Wisma Atlet, tempat khusus isolasi. Mesjid di Kebun Jeruk ketat dijaga polisi dan tentara. (7)
Anggota Jamaah Tabligh yang terkena virus terus meningkat. Awalnya hanya 3 orang, bertambah menjadi 39 orang, lalu 74 orang (8).
Handphone Iman masih tak bisa dikontak.
Kembali kulihat lukisan itu. Kembali kubaca tulisan dari Iman itu: “My brother is always my superhero.”
Sedih kutahan. “Iman adikku, sayang. Di hadapan Virus Corona, kakakmu tak bisa menjadi superhero. Kakak tak berdaya.”
Malam semakin kelam. Hatiku lebih kelam.***
April 2020
1). Catatan kaki dalam cerpen esai fungsinya sangat sentral. Catatan kaki itu sumber kisah. Sementara teks cerpen hanyalah dramatisasi, fiksionalisasi dari kisah sebenarnya, agar kisah itu lebih menyentuh, lebih menjadi pembelajaran.
2). Cerpen esai ini berangkat dari peristiwa sebenarnya, yang kemudian difiksikan. Lebih dari dua ratus jemaah mesjid dikarantina, di Jakarta. Termasuk di dalamnya, 78 warga negara asing. Link: https://www.vivanews.com/amp/berita/nasional/42832-ratusan-orang-dikarantina-di-masjid-kebun-jeruk-tiga-positif-corona
3) Gaya hidup Jamaah Tabligh banyak di bahas di makalah ini. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/visualita/article/download/1115/pdf/
4) Lihat sumber di catatan no 3
5) Lihat sumber di catatan no 3
6) Banyak negara yang terjangkit virus corona melalui Jamaah Tabligh diberitakan di aneka sumber:
7) Polisi dan tentara banyak menjaga masjid. https://amp.sukabumiupdate.com/detail/ragam-berita/nasional/67138-Tentara-Ikut-Berjaga-Begini-Kondisi-144-Jemaah-Tablig-Diisolasi-di-Masjid
8) Jumlah Jamaah terkena Virus Corona bertambah. https://www.google.co.id/amp/s/www.tagar.id/73-jemaah-tabligh-masjid-kebon-jeruk-positif-corona/amp/










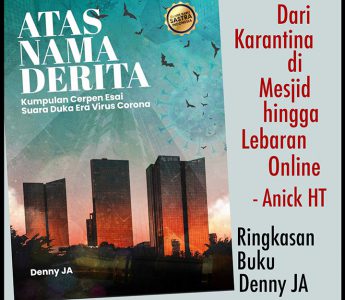












Comment