KOPI, Bekasi – Kata adalah sabda. Tapi ketika kata-kata tersusun menjadi kalimat dan kalimat menjadi bahasa, tiba-tiba maknanya berubah absurd. Absurditas itu berkembang sejalan dengan kompleksitas problem kehidupan manusia.
Kata dan sabda adalah firman. Firman adalah suara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Sayang, di dunia yang penuh absurditas, makna suci kata dan sabda runtuh satu persatu. Struktur sosial, politik, dan ekonomi yang tercerabut dari firman telah merubah kata yang penuh makna menjadi kata yang sia-sia. Bahkan kata menjadi malapetaka yang menjerumuskan manusia ke dalam bahaya.
Bahasa telah diselewengkan dari tujuan sucinya untuk mengkomunikasikan kebenaran. Dan kini, bahasa telah berubah menjadi instrumen penindasan. Firman yang melekat dalam bahasa, telah hancur dilindas ambisi dan nafsu angkara murka manusia.
“Bila dalam kehidupan telah muncul kata suicide, homocide, dan genocide, maka dalam bahasa pun telah muncul semanticide,” tulis Thomas Szasz dalam bukunya The Second Sin. Semanticide, tulis Szasz, telah menghancurkan makna kata yang sebenarnya. Dampaknya: perekayasa semanticide menjadi pemegang otoritas kebenaran.
“Kata bisa bermakna ke sana ke mari dan liar, tergantung keluar dari mulut siapa,” ujar Soetardji Calzoum Bachri – “presiden penyair” asal Rengat (Riau). Karenanya, Soetardji mendeklarasikan pembebasan kata dari makna. Menurut Sutardji, di zaman yang penuh absurditas dan kemunafikan, kata harus dibebaskan dari makna. Biarkan kata berubah jadi mantra yang magis untuk kembali pada kebenaran awalnya.
Semantisida tumbuh subur dalam masyarakat yang tidak transparan, totaliterian, munafik, dan haus kekuasaan. Semantisida tak hanya mengganjal saluran komunikasi dan kesaling-pengertian – tapi juga mengkamuflase praktik kezaliman dan kecurangan.
“Kita harus berperang menentang bahasa,” tulis sastrawan kulit hitam Ossie Davis dalam The English is My Enemy. Bahasa Inggris – tulis Davis – adalah bahasa pencipta rasialisme. Ia mengumpulkan kata white dan black serta turunannya dalam bahasa Inggris. Dari 130-an kata white dan black serta derivasinya, hampir semua kata white bermakna baik. Sementara kata black nyaris semuanya buruk. Davis mencatat, 20 kata black berkonotasi rasialisme secara mencolok seperti negro, negress, nigger, darky, blackmoor, dan lain-lain.
Apa yang ditulis Davis, kini berada di tengah kita. Kata kampret, cebong, kadal gurun, dan radikal, misalnya, kini telah berubah makna dalam Bahasa Indonesia. Banyak kata dalam bahasa Indonesia telah berubah menjadi instrumen “Jin Ifrit” yang haus kekuasaan dan darah. Bahkan, ia menjadi perusak budaya dan etnografi nusantara. Kata jilbab, niqab, syar’i, kafir, dan musyrik misalnya, telah menjadi instrumen penindasan terhadap orang-orang Indonesia yang berbusana kebaya dan pakaian etnis lain serta non-Islam yang hidup di tengah komunitas kaum islamis intoleran. Kata-kata tersebut telah menjadi semantisida yang “membunuh” logika dan budaya.
“Yesus itu radikal,” tulis Efron Bayern dalam statusnya di facebook Kavir untuk merespon banjirnya kata radikal yang pejoratif di medsos, sambil menunjukkan buku “Yesus Sang Radikal” karya R.T. France.
“Betul Efron,” komen saya. Tapi radikalnya Yesus adalah radikal kasih. Yesus adalah radikalis altruis. Yesus mengorbankan diri untuk keselamatan umat. Yesus adalah sang radikal prokreasi dan prokehidupan. Bukan radikal suicide bombing dan membunuh orang yang tak sepaham.
Muhammad, seperti halnya Yesus, juga mendoakan keselamatan terhadap orang-orang yang menyakitinya. Itulah sebabnya, Tuhan menyatakan, Muhamad diutus untuk menjadi rahmat, bukan laknat bagi manusia.
Firman Tuhan tersebut mengingatkan bahwa makna Islam adalah rahmat yang indah dan menyegarkan untuk berkembangnya kehidupan. Bukan laknat yang menakutkan dan prokematian. Sejak awal, Tuhan sudah memblok penyebar semanticide terhadap kata Islam. Tapi sayangnya, banyak orang Islam yang memilih sebaliknya.
Kini, penyelewengan kata radikal sudah sedemikian parah, sehingga radikalisme para Rasul yang prokreasi dan prokasih berubah menjadi radikal proambisi dan promati. Radikal yang bermakna prokehidupan, di era kemunafikan dan monster kekuasaan atas nama Tuhan, berubah menjadi prokematian. Dan prokematian itulah tujuan semanticide.
Padahal firman Tuhan memberi petunjuk: siapa orang yang membunuh seorang manusia tak bersalah, dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka pahalanya sama dengan memelihara seluruh umat manusia (Al-Maidah 32).
__________
NB. Artikel di atas pernah dimuat di koran Berita Buana 28 Oktober 1991, waktu saya bekerja di Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta. Saya edit lagi sesuai isu yang berkembang saat ini.












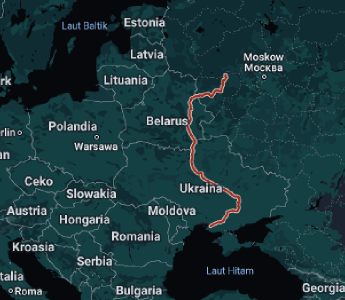















Comment